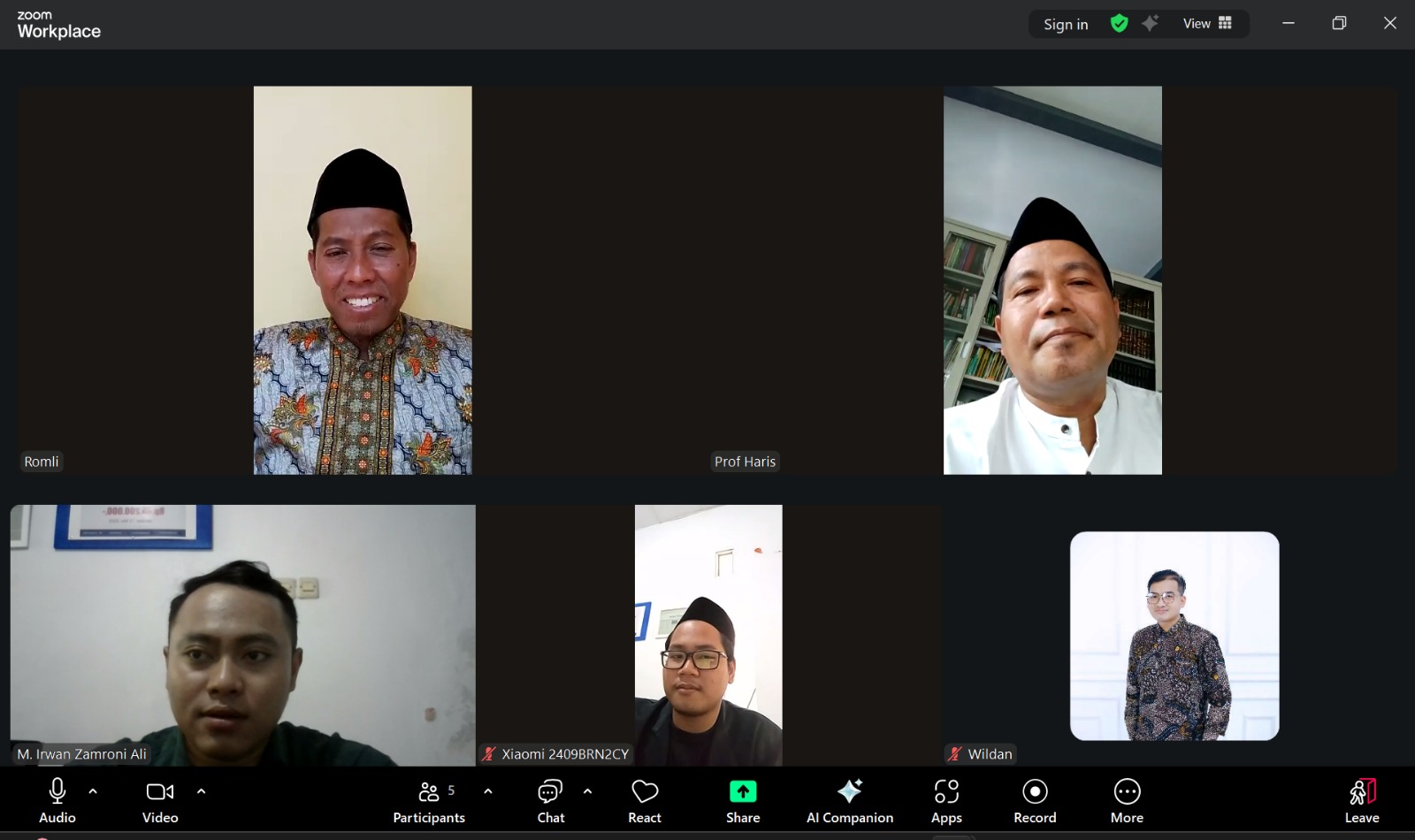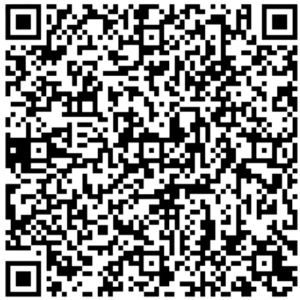Oleh: Abdul Moqsith Ghazali
Tubuhnya kecil, berkulit kuning langsat. Tatapan matanya tajam. Berpenampilan sederhana. Suaranya lembut dan timbrenya tipis. Terkesan hemat bicara. Intonasinya datar. Pembawaan dirinya tak mengecoh orang untuk segera memerhatikannya. Namun, ketika ia tampil sebagai pembicara di forum-forum seminar, audiens tak bisa mengabaikannya. Ia tampak powerfull. Di balik tubuhnya yang ringkih, tersimpan energi intelektual luar biasa. Itulah KH Afifuddin Muhajir, wakil pengasuh pesantren Sukorejo Asembagus Situbondo.
Saya berjumpa dengan banyak orang yang mengakui kedalaman ilmu dan keluasan wawasan Kiai Afif. Bahkan, jauh sebelum saya belajar kitab kuning kepada Kiai Afif (begitu ia biasa disapa sekarang), saya sudah mencium keharuman namanya dari alumni pesantren Sukorejo yang mengajar di pesantren kepunyaan orang tua saya. Mereka berkata bahwa Kiai Afif (saya dulu memanggilnya “Ustad Khofi”) mendapatkan ilmu ladunni, yaitu ilmu yang dikaruniakan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta’ala. Tak terkecuali ayah saya (KH Ghazali Ahmadi) dan paman saya (alm KH Qasdussabil Syukur) yang pernah mengajar Kiai Afif di pesantren Sukorejo mengakui kealiman Kiai Afif.
Karuan saja, ketika saya dikirim orang tua untuk belajar di pesantren Sukorejo, Kiai Afif adalah orang pertama yang saya “buru”. Saat itu ia sudah menjadi ustad dan belum menikah. Ia tinggal di sebuah kamar-asrama yang tak jauh dari kamar-asrama saya. Setiap hari saya bisa melihat sosoknya. Kiai Afif yang ketika berjalan selalu menunduk-menatap tanah itu mungkin tak menyadari bahwa ada banyak santri seperti saya yang selalu memerhatikannya. Sambil beradaptasi dengan lingkungan sosial baru di pesantren, saya coba mendengarkan presentasinya di forum bahtsul masa’il dan kemudian mengikuti pengajiannya.
Biasanya bahkan hingga sekarang Kiai Afif mengajar kitab secara bandongan di sebuah mushala depan kediaman KH As’ad Syamsul Arifin. Kitab yang dibacanya adalah kitab-kitab marhalah `ulya seperti al-Iqna`, Fathul Mu`in, Fathul Wahhab, Ghayatul Wushul, dan lain-lain. Saya yang sudah dibekali ilmu-ilmu dasar keislaman oleh orang tua tak merasa terlalu sulit untuk mengikuti pengajian Kiai Afif. Saya hanya terpukau dengan kefasihan dan kepiawaiannya dalam menerjemahkan dan mengulas kitab kuning. Kiai Afif coba mengartikan kitab kuning dengan bahasa-bahasa akademik-ilmiah. Sambil mengaji, saya kerap mendengar darinya istilah-istilah seperti “argumen”, “aksioma”, “tekstual”, “kontekstual”, dan lain-lain. Itu salah satu kelebihan Kiai Afif dibanding para ustad lain ketika itu.
Setelah Kiai Afif banyak beraktivitas di luar terutama sejak menjabat Katib Syuriyah PBNU, publik Islam mulai mengetahui kealiman Kiai Afif di bidang ushul fikih. Tak sedikit dari mereka yang bertanya, di mana Kiai Afif belajar ushul fikih? Saya tak segera menemukan jawabannya. Ini karena Sukorejo sendiri, tempat Kiai Afif belajar, tak dikenal sebagai pesantren ushul fikih. Sukorejo lebih banyak berkonsentrasi pada pengajian ilmu fikih dan nahwu-sharaf. Sekalipun ada pengajian ushul fikih, durasinya cukup kecil jika dibandingkan dengan bidang-bidang lain. Sukorejo pun saat itu tak banyak mengoleksi buku-buku ushul fikih dari lintas madzhab. Dengan kondisi ini, agak susah membayangkan lahirnya seorang pakar ushul fikih dari Sukorejo.
Kiai Afif tak pernah belajar di luar, baik di timur apalagi di barat. Seluruh jenjang studinya, mulai dari Madrasah Ibtida’iyyah hingga strata satu, diselesaikan di Sukorejo. Ketika saya tanya, “Kepada siapa Kiai Afif belajar ushul fikih?” Ia menjawab, “Saya pernah mengaji kitab Lubbul Ushul pada KH Qasdussabil Syukur. Selebihnya saya belajar sendiri”. Ini menunjukkan bahwa kealimannya di bidang ushul fikih ditempuh melalui kerja keras dan ketekunan. Peran Kiai Qasdussabil adalah mengajarkan teks utama ushul fikih, Lubbul Ushul, kepada Kiai Afif. Tapi, pendalamannya dilakukan secara otodidak. Dengan perkataan lain, ia memperluas sendiri bacaan ushul fikihnya, dengan melahap ar-Risalah karya Imam Syafi’i, al-Mustashfa min `Ilmil Ushul karya al-Ghazali, al-Muwafaqat fi ushulis Syari’ah karya as-Syathibi, al-Ihkam fi Ushulil Ahkam karya al-Amidi. Namun, dalam amatan saya, kitab ushul fikih yang paling disukai sekaligus dikuasainya tampaknya adalah Jam’ul Jawami’ karya Tajuddin as-Subki itu.
Baru pada perkembangan berikutnya Kiai Afif melengkapi diri dengan referensi ushul fikih modern. Kiai Afif membaca buku-buku ushul fikih mulai dari karya Abdul Wahhab Khallaf, Abu Zahrah, Muhammad Khudhori Bik, Wahbah az-Zuhaili hingga merambah pada buku-buku karya `Allal al-Fasi, Ahmad ar-Raysuni, dan Jasir Audah yang banyak mempercakapkan soal maqashid al-syari’ah dan fiqhul maqashid. Dengan penguasaan yang komprehensif atas literatur-literatur itu, Kiai Afif makin kukuh sebagai seorang faqih dan ushuli. Dan kedudukannya sebagai ahli fikih telah dibuktikan Kiai Afif dengan menulis buku fikih berbahasa Arab dengan judul Fathul Mujibil Qarib, syarah terhadap kitab at-Taqrib karya Abu Syuja’ al-Isfahani.
Di bidang ushul fikih, keahlian Kiai Afif memang tak terbantahkan. Puluhan makalah terkait metode istinbathul ahkam telah selesai ditulisnya. Ia menulis buku dengan judul as-Syari’ah al-Islamiyah baynats Tsabat wal Murunah. Menarik, Kiai Afif menjadikan ushul fikih sebagai sebuah perspektif untuk merespons persoalan-persoalan keislaman kontemporer. Ia berbicara tentang negara Pancasila, Islam Nusantara, dan lain-lain dari sudut pandang ushul fikih. Ia juga menjadikan ushul fikih sebagai perangkat metodologis untuk mendinamisasi fikih Islam. Untuk kepentingan dinamisasi pemikiran Islam itu Kiai Afif intens berdiskusi dengan para pemikir gaek lain di NU seperti KH Ahmad Malik Madani, KH Masdar Farid Mas’udi, KH Said Aqil Siroj, KH Husein Muhammad, dan lain-lain.
Di tangan orang-orang seperti Kiai Afif ini, ushul fikih adalah sumur yang airnya tak pernah kering untuk ditimba. Jika ada yang mengkhawatirkan bahwa sepeninggal Kiai Sahal Mahfudz NU akan dilanda kelangkaan ahli ushul fikih, maka fenomena Kiai Afif ini akan menampik kekhawatiran itu. Tentu Kiai Afif tak sendirian. Ada banyak kiai dan intelektual muda NU lain yang memiliki penguasaan memadai tentang ushul fikih. Hanya yang kita “tagih” dari orang-orang seperti Kiai Afif adalah konsistensinya untuk terus menulis dan berkarya. Mengikuti sunnah Kiai Sahal Mahfudz yang banyak menulis buku seperti membuat syarah terhadap al-Luma’ dan Ghayatul Wushul, saya berharap Kiai Afif juga mau menulis banyak buku termasuk membuat syarah terhadap kitab-kitab ushul fikih lain seperti Jam’ul Jawami yang dikenal sangat susah dipahami itu.
Abdul Moqsith Ghazali, alumnus pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Situbondo