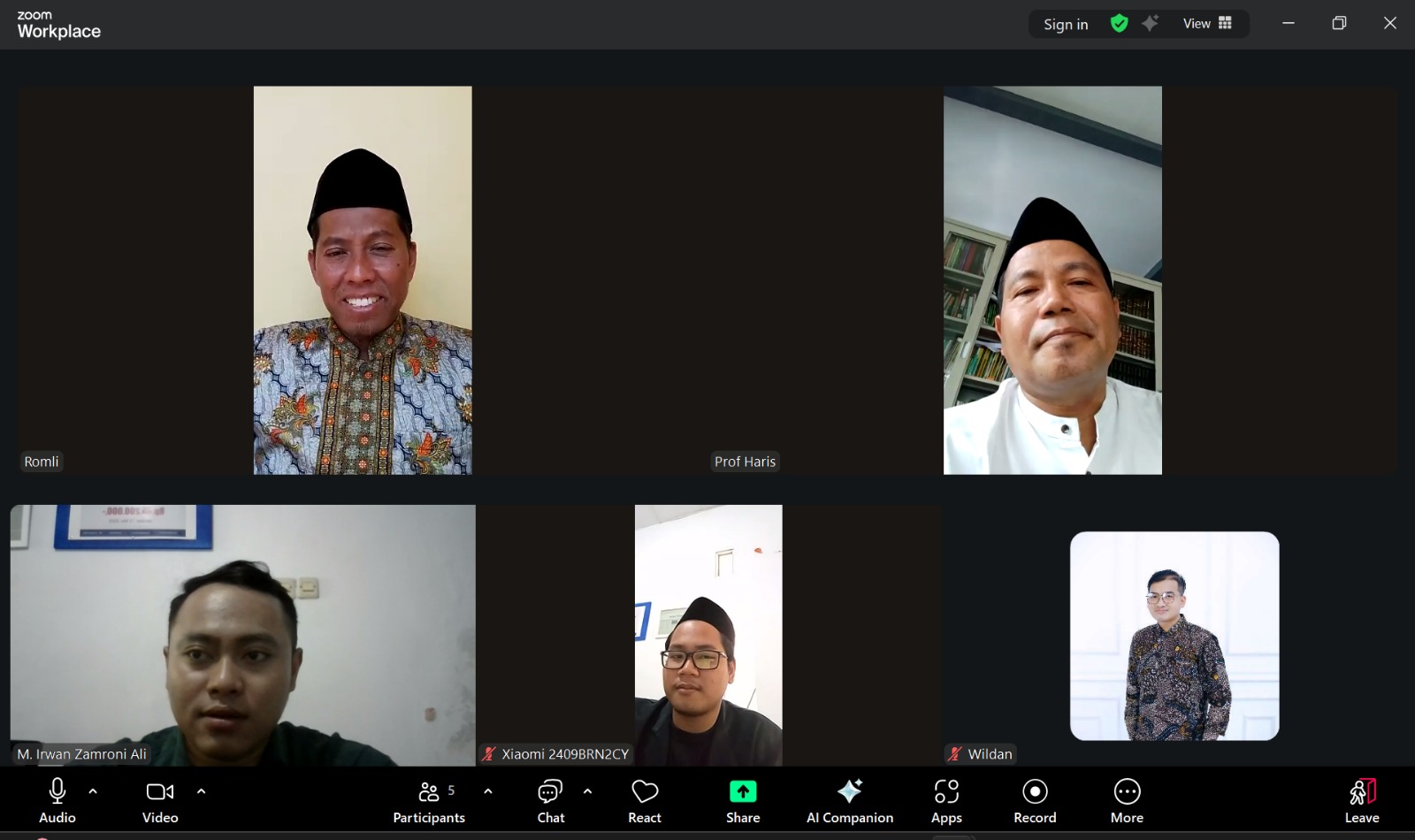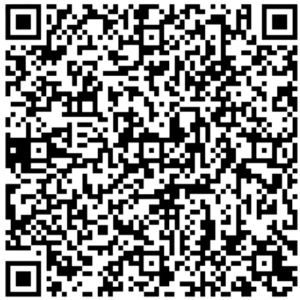Oleh: M.N. Harisudin
Dosen Pasca Sarjana IAIN Jember
Katib Syuriyah PCNU Jember
Salah satu hal yang diacu dalam fiqh, adalah bahwa seseorang tidak boleh beralasan melakukan larangan Allah Swt. atau ia meninggalkan perintah-Nya dengan alasan tidak tahu. Misalnya, seorang yang melakukan perzinahan tidak boleh mengatakan “ Saya tidak tahu kalau melakukan zina itu dilarang”. Orang yang melakukan korupsi tidak boleh berkata: “Saya tidak tahu kalau korupsi itu dilarang”. Demikian juga, tidak diperhitungkan orang yang mengatakan:” Saya tidak tahu kalau sholat lima waktu itu diwajibkan”. Atau seseorang yang tidak membayar zakat tidak bisa berkata “Maaf, saya tidak tahu kalau zakat itu wajib hukumnya”. Dan demikian seterusnya.
Semua alasan yang dikemukakan di atas, dalam pandangan syara’, tidak berlaku. Artinya, alasan itu tidak menggugurkan dosa seseorang yang melakukan larangan Allah Swt. atau meninggalkan perintah-Nya. Dengan kata lain, ia tetap berdosa. Demikian ini karena hukum Islam berlaku umum. Siapapun seorang muslim yang mukallaf (baligh dan berakal), maka wajib baginya untuk melakukan perintah Allah Swt. dan menjauhi larangan-Nya. Begitu hukum Islam diundangkan, maka hukum Islam berlaku secara universal tanpa kecuali.
Berkaitan dengan ketidaktahuan ini, Allah Swt. berfirman: “Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus.” (QS. An Nisa: 165). Dalam hadits, Rasulullah Saw. juga bersabda: “Demi Dzat yang jiwa Muhammad di tangan-Nya!! Tidaklah seorang dari umat ini, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani yang mendengar tentangku kemudian ia tidak beriman dengan syariat yang aku bawa kecuali pasti ia termasuk penghuni neraka” (HR. Muslim: 153).
Prof. Abdul Wahab Khalaf, Guru Besar Syari’ah di Universitas al-Azhar Mesir, dalam Kitab Ilmu Ushul al-Fiqh, mengatakan: Wa yulahadzu annal muraada bi’ilmil mukallafi bima kullifa bihi imkaanu ‘ilmihi bihi la ilmuhu bihi fi’lan. Fa mata balaghal insanu ‘aqilan qaadiran ‘ala an ya’rifal ahkam as-syar’iyyata binafsihi au bisuali ahlidzikri ‘anha, u’tubira ‘aliman bima kullifa bihi wa nafadzat alaihi al-ahkaamu wa ulzima bi atsaariha wala yuqbalu minhu al-I’tidzaaru bijahliha. (Abdul Wahab Khalaf: 1948, 129).
Artinya: Dan perlu diperhatikan bahwa yang dimaksud dengan “mengetahuinya mukallaf” dengan sesuatu yang dibebankan (taklif) padanya adalah “potensi mengetahuinya mukallaf” (imkanufi’lihi) dan bukan “mengetahuinya mukallaf secara faktual” (la ilmuhu bihi fi’lan). Oleh karena itu, ketika seorang sudah baligh, berakal dan mampu mengetahui hukum syar’i baik dengan dirinya atau bertanya pada orang yang tahu, maka ia dianggap sebagai orang yang tahu terhadap apa yang ditaklifkan padanya, berlakulah hukum padanya dan ditetapkan dampak hukum padanya. Selanjutnya, ketidaktahuan dia terhadap hukum tidak dapat diterima.
Walhasil, kata kuncinya disini adalah bahwa hukum Islam berkaitan dengan potensi mengetahuinya seseorang. Seorang yang sudah baligh dan berakal—dalam pandangan syar’i—adalah dipandang sebagai orang yang mengetahui hukum syar’i. Tidak peduli: apakah ia benar-benar tahu terhadap hukum Allah Swt. atau tidak mengetahuinya. Potensi inilah yang diperhitungkan dalam hukum Islam. Karena itu, orang yang memiliki potensi ini, sudah dikenai beban hukum-hukum Allah Swt.
Sesungguhnya, berlaku hal yang sama dalam hukum positif yang berlaku di negara ini. Seorang pengendara mobil yang ditangkap polisi tidak bisa berdalih bahwa ia tidak tahu kalau mengendarai mobil tanpa sabuk pengaman itu dilarang. Ia tidak bisa berkata:”Maaf pak polisi. Saya tidak tahu kalau harus menggunakan sabuk pengaman ketika menegendarai mobil ”. Dalih ini tidak bisa diterima. Pelanggar mobil ini tetap kena denda. Karena begitu undang-undang Satlantas disahkan dalam lembaran negara, maka berlakukah hukum lalu lintas. Semua orang di negara ini dianggap tahu tentang undang-undang ini, meskipun secara de facto, dia belum pernah membaca undang-undang satlantas ini.
Hanya saja, soal ketidaktahuan seorang mukallaf ini, ada beberapa pengecualian yang dalam fiqh disebut dengan jahil ma’dzur (Ketidaktahuan yang ditoleransi). Dalam pandangan fiqh, ada dua orang yang dikatakan jahil ma’dzur, yaitu: Pertama, seorang yang hidup jauh dari ulama. Kedua, orang yang baru masuk Islam. (Bughyatul Murtasyidin: 89). Kedua orang ini dimaafkan jika melanggar aturan hukum Islam. Sebaliknya, selain yang dua ini, tidak dapat dikategorikan sebagai jahil ma’dzur alias tidak diperhitungkan ketidaktahuannya.
Wallahu’alam.*