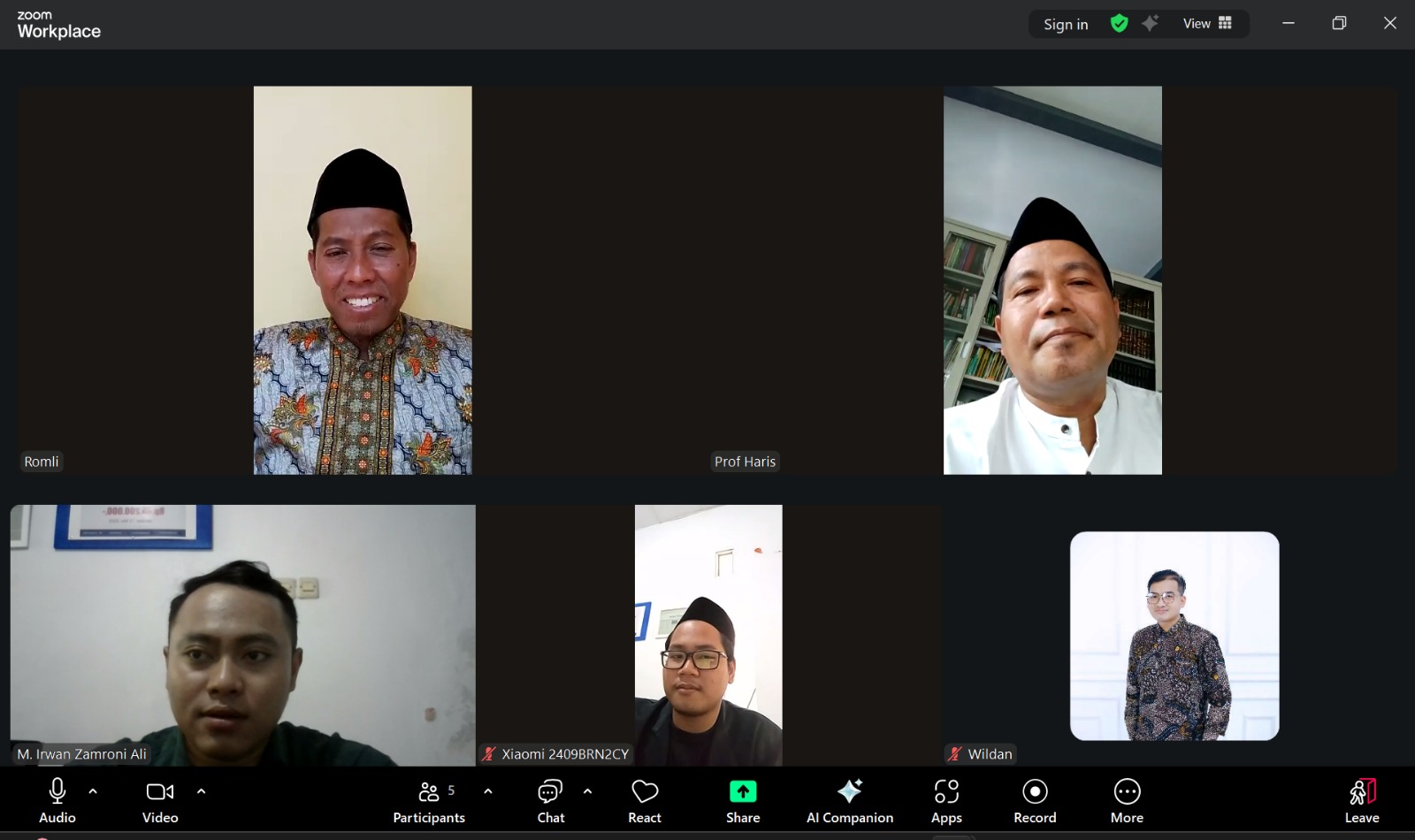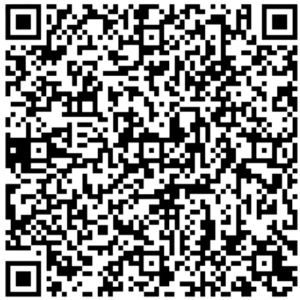Oleh: M. Noor Harisudin
Heboh di media massa beberapa saat yang lalu tentang tarif yang tinggi dalam “ceramah agama” sejumlah dai di Jakarta, menarik untuk dicermati. Tarif tinggi ini memang luar biasa tinggi karena mencapai angka nominal 150-an juta. Sang ustadz yang menjadi mubaligh itu sejak awal juga mematok harga yang tinggi tersebut di muka. Artinya, dalam perjanjian disebutkan angka honor untuk ceramah agama tersebut. Pertanyaan fiqhnya adalah: bagaimana hukum penceramah agama mematok tarif ceramah agama dengan harga yang tinggi tersebut?
Dalam hal mematok tarif ceramah agama, para ulama sepakat untuk tidak boleh. Artinya haram hukumnya bagi penceramah agama mematok tarif dalam ceramah agama dengan harga berapapun, baik tinggi ataupun rendah. Larangan mematok harga ceramah agama adalah khusus untuk sang penceramah. Karena ceramah agama adalah sebentuk syi’ar agama yang tidak boleh “dikomersial-kan”. Dakwah Islam adalah bentuk perjuangan yang semestinya tidak ada imbalan.
Larangan ini didasarkan pada firman Allah Swt. yang berbunyi: “Hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku ini. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah Swt yang menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti ? (QS. Hud: 51). Dalam ayat yang lain, Allah Swt juga berfirman: “Katakanlah aku tidak meminta upah sedikitpun padamu atas dakwahku dan aku bukan termasuk orang yang mengada-adakan. (QS. Shad: 86). Artinya, upah atas dakwah Islamiyah merupakan tanggungan dari Allah Swt. Karena itu, mematok harga ceramah agama adalah bertentangan dengan subtansi dua ayat ini.
Yang diperbolehkan adalah honor ceramah agama yang tidak dipatok oleh sang penceramah. Dengan demikian, berapapun honor yang diberikan, jika tidak dipatok dari penceramah, ulama fiqh –dalam hal ini Madzhab Syafi’i dan Maliki–memperbolehkannya. Dengan kata lain, jika yang mematok atau menentukan bisyaroh untuk penceramah (misalnya) adalah panitia acara, maka hukumnya tidalahk haram.
Dalam bahasa fiqh, ini disebut dengan al-ujroh ‘alat tha’ah. Seperti yang disebut Sayid Sabiq dalam Fiqh as-Sunah dan Wahbah Az-Zuhaily dalam al-Fiqh al-Islamy wa Adilaltuhu, al-ujrah ‘alat thaa’ati selama tidak ditentukan atau dipatok (lam tata’ayyan) diawal, hukumnya diperbolehkan karena merupakan hajat manusia (lijahatin nas). Bagaimanapun juga, seorang penceramah juga membutuhkan sandang, pangan, papan, dan kendaraan untuk mobilitas dakwah Islamiyahnya. Selain itu, ada hadits-hadits yang menunjukkan kebolehan mengambil upah dari mengajar al-Qur’an, dan sebagainya.
Meski diperbolehkan, dalam pandangan saya, kondisi ini merupakan kondisi yang tidak ideal. Saya menyebutnya kurang afdlol atau kurang ideal. Idealnya penceramah agama adalah para pejuang Islam yang tanpa pamrih, tanpa bisyaroh dan tanpa amplop. Para pejuang yang mengajarkan Islam dengan tanpa bisyarah. Ini adalah konsep ideal karena dengan tanpa pamrih, umat yang menjadi obyek ceramah agama akan mudah mendapatkan petunjuk. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Yasin ayat 21 : Ittabiu man la yasalukum ajran wahum muhtadun. Artinya: Ikutlah pada mereka yang tidak memintamu upah (atas dakwah mereka) sementara mereka adalah orang yang diberi petunjuk.
Logikanya, bagaimana umat akan “terkesima” dan juga menerima ajaran kebaikan yang ditebar sang penceramah jika sejak awal sang penceramah minta upah atas ceramah agamanya? Karena itulah, Rasulullah Saw. tidak pernah meminta ujrah berapapun atas ceramah (dakwahnya) pada umatnya. Kebenaran agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. tidak pernah diganti upah yang sebanding. Rasulullah Saw. telah mencukupkan pahala dari Allah Swt atas seluruh dakwah Islam yang beliau sampaikan pada umatnya.
Karena niat tulus dan tanpa pamrih Rasulullah Saw. dalam bertabligh (dakwah Islamiyah), maka hasilnya pun jelas: umat secara faktual menerima dakwah yang telah diberikan Rasulullah Saw. Dengan kata lain, tabligh tanpa amplop ini berbanding lurus dengan hidayah yang diterima umatnya. Jika Rasulullah Saw. menarik upah atas dakwahnya pada umat, pastilah yang terjadi akan lain dan Islam tidak berkembang dahsyat seperti sekarang.
Saya sendiri mengapresiasi para penceramah yang mendarmakan dirinya untuk hidup bertabligh tanpa bisyaroh, tanpa amplop. Sebagian beberapa kawan di kota lain, bukan hanya ia tidak mau menerima bisyaroh dan amplop, ia malah mengeluarkan koceknya untuk membeli kebutuhan jama’ah majlis taklim. Subhanallah. Di Banyuwangi, ada kawan penceramah yang selalu membelikan sarung, baju takwa dan mukena untuk dua ribu jama’ah majlis taklim setiap tahunnya. Di kota lain, ada penceramah yang menyiapkan konsumsi untuk jama’ahnya setiap kali ceramah.
Lalu, bagaimana dengan kita ?
Wallahu’alam. **
M.N. Harisudin, adalah Dosen Pasca Sarjana STAIN Jember, Katib Syuriyah PCNU Jember, Wakil Sekretaris YPNU Jember dan Wakil Ketua Lajnah Ta’lif wa an-Nasyr NU Jawa Timur. Selain itu, menjabat sebagai Deputi Salsabila Group Surabaya.