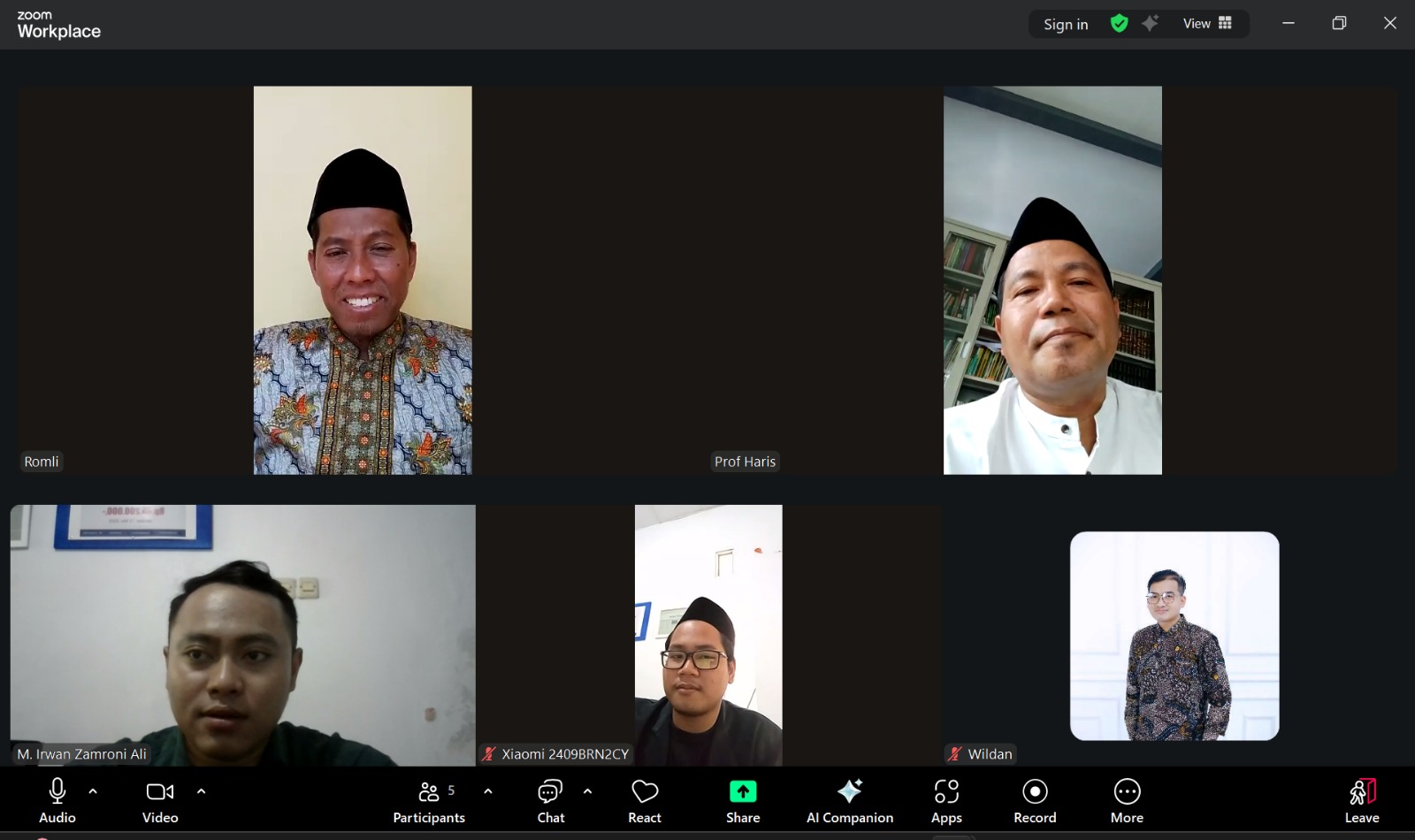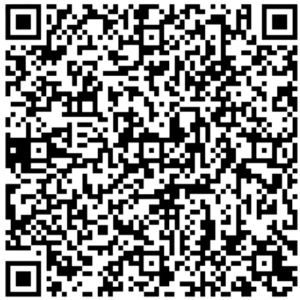oleh M. Noor Harisudin
Dosen IAIN Raden Paku Jember
Pengasuh Ponpes Ar-Riayah Mangli Kaliwates Jember
Wakil Ketua PW Lajnah Ta’lif wa an-Nasyr NU Jawa Timur
Secara konsep, Indonesia sudah final. Namun, secara praktek, Indonesia masih belum (dan jauh dari) final. Dalam proses pencapaian cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang final, aral dan hambatan senantiasa melintang. Cita-cita juga tidak bisa seratus persen digapai. Last but not least, cita-cita ini memang suatu saat nanti akan terwujud, kendati yang kita lihat baru berapa persennya saja. Yang kita lakukan secara kolektif tanpa melihat ras, agama dan aliran adalah melakukan ikhtiar sekuat mungkin dan yang terbaik untuk mencapai cita-cita tersebut.
Belakangan marak gerakan yang ingin mengubah haluan negara Indonesia yang kita cintai ini. Mereka ingin mengganti Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini dengan sistem khilafah. Khilafah, dalam imaginasi mereka, adalah solusi atas semua problematika kehidupan. Sebagian yang lain mengusung perda syari’at Islam sebagai panacea atas pelbagai problematika hidup yang kian kompleks dan akut. Sebagian yang lain ingin menggantinya dengan kembali pada ideologi komunisme. Di sinilah, tulisan ini serasa menemukan momentumnya.
Memang, sebagian pemikir Islam memilih untuk tidak mengkaitkan agama (Islam) dengan negara. Agama dalam pandangan ini adalah adalah satu hal, sementara negara adalah hal lain yang berbeda. Seperti Nawal el Saadawi, seorang sastrawan besar di Mesir yang pernah melontarkan kritik keras terhadap apa yang disebut Negara Islam. Menurutnya, negara tidak punya jenis kelamin agama (baca: tidak beragama) karena yang beragama adalah manusia. Dalam hal ini, Nawal el Saadawi menyatakan: “ People who think that state is Islam have not studied Islam. The state is nothing to do with Islam”. (The Jakarta Post, November, 27, 2006).
Namun, saya tidak sepenuhnya sepakat dengan Nawal El Saadawi karena secara de facto masyarakat Islam sudah bersinggungan dengan politik Islam sejak masa Rasulullah Saw. hingga masa sekarang. Tak mengherankan jika Montgomory Watt dalam buku Muhammad Prophet and Statesman mengatakan bahwa Muhammad bukan hanya seorang nabi, namun juga seorang kepala Negara (negarawan). (W. Montgomery Watt: 1961, 94-95). Di samping itu juga, jika kita tengok ke belakang, kala Muhammad menjadi kepala negara, semua unsur negara modern sudah terpenuhi seperti wilayah, penduduk, pemerintahan dan juga kedaulatan.
Di sinilah, makanya saya lebih senang menggunakan perspektif paradigma simbiotik (symbiotic paradigm). Dalam paradigma ini, posisi agama dan negara berhubungan secara simbiotik yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Agama memerlukan negara karena dengan negara (daulah), agama dapat berkembang. Demikian sebaliknya, negara juga memerlukan agama karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spritualnya. Sehingga, dalam paradigma ini, baik agama dan negara saling menguatkan dan mengukuhkan.
Paradigma ini senada dengan pandangan Gus Dur yang menyebut agama sebagai ruh atau spirit yang harus masuk ke dalam negara. Sementara, bagi mantan Presiden RI ke-4 tersebut, negara adalah badan atau raga yang mesti membutuhkan negara. Dalam konsep Gus Dur, keberadaan negara tidak bisa dilihat semata-mata hasil kontrak sosial (yang sekuler), namun, bahwa negara dipandang sebagai jasad yang membutuhkan idealisme ketuhanan. Agama, dalam konteks ini, lebih ditempatkan sebagai subtansi untuk menuju cita-cita keadilan semesta. (Masdar F. Mas’udi: 1993, xiv-xvi).
Pilihan paradigma di atas jelas menegasikan dua paradigma lain yang berada di kutub ekstrem. Pertama, paradigma integralistik yang memandang agama dan negara menyatu. Wilayah agama meliputi politik atau negara. Negara selain lembaga politik juga lembaga keagamaan. Pandangan yang sering disebut dengan istilah al-Islam din wa daulah ini dipraktekkan oleh Syi’ah. Kedua, di ekstrem yang lain, paradigm sekuler yang mengajukan pemisahan agama dan negara. Paradigma yang dimotori oleh Ali Abd ar-Raziq ini (1887-1966 M) menolak pendasaran negara pada agama (Islam). Pemikiran paradigma ini didasarkan asumsi bahwa Muhammad murni sebagai pendakwah Islam dan sama sekali tidak pernah menjadi kepala Negara.
Bertolak dari paradigma yang saya ajukan di atas ini, maka jika ditanya: apakah cita-cita Politik Islam, saya mengatakan bahwa cita-cita politik Islam adalah sama dengan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita Indonesia merdeka adalah, seperti kata Soekarno, menjadi “jembatan emas” untuk mencapai cita-cita negara Indonesia. Adapun cita-cita negara ini, sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, adalah untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia akan tercapai. Pada tahap selanjutnya, cita-cita tersebut diderivasikan lebih lanjut dalam batang tubuh UUD 45, seperti kesamaan di depan hukum, kebebasan berserikat dan berpolitik, serta mengenai kesejahteraan sosial seperti tanggung jawab negara terhadap rakyat miskin, serta mengenai demokrasi ekonomi.
Secara normatif, cita-cita kemerdekaan ini sejalan dengan cita-cita politik Islam. Al-Mawardi dalam Al-Ahkam as-Sulthaniyah misalnya menyebut tujuan sebuah negara adalah lihiraasatiddin wa siyasatid dunya. (Abu Hasan Al-Mawardi: tt, 6). Artinya, untuk memelihara agama dan mengatur dunia. Secara derivatif, pandangan ini dikukuhkan oleh Imam Al-Ghazali yang dikutip Abu Zahro yang menyebut ad-dlariyatul khams sebagai pilar yang mesti diacu oleh sebuah Negara. Yakni., memelihara agama (hifdz ad-din), memelihara jiwa (hifdz an-nafs), memelihara akal (hifd al-aql), memelihara keturunan (hifdz an-nasl) dan memelihara harta (hifdz al-mal). (Muhammad Abu Zahro: 1994, 548-553)
Kekuasaan negara, oleh karena itu, dikukuhkan untuk pemenuhan lima hal pokok yang dijaga dalam Islam ini. Sebut misalnya keberpihakan pada kaum miskin (mustadz’afin) dalam bentuk pelayanan kesehatan di negeri ini harus dilihat dalam perspektif hifdz an-nafs (memelihara jiwa). Demikian juga pengutamaan anak bangsa dalam urusan kesejahteraan dibanding negeri asing ketika menentukan mana yang lebih penting: perusahaan anak negeri atau perusahaan asing yang mesti mengelola, harus dilihat dalam konteks hifdz al-mal warga negara Indonesia.
Hanya saja, secara realitas, apa yang dicita-citakan masih jauh dari kenyataan. Alih-alih menuju cita-cita kemerdekaan ini, kadang kala cita ini dibelokkan ke arah yang bertolak belakang dengan cita-cita kemerdekaan. Neo-liberalisme yang menggurita, korupsi yang meraja lela, pemenuhan hak orang miskin yang terabaikan, dan segudang masalah lain, adalah bentuk anti klimaks cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Sudah semestinya energi bangasa ini kita fokuskan untuk menggapai cita-cita itu, bukan malah mengganti ideologi NKRI dengan sistem khilafah dan atau komunisme.
Dengan kata lain, secara konsep, Indonesia sudah final. Namun, secara praktek, Indonesia masih belum (dan jauh dari) final. Dalam proses pencapaian cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang final, aral dan hambatan senantiasa melintang. Cita-cita juga tidak bisa seratus persen digapai. Last but not least, cita-cita ini memang suatu saat nanti akan terwujud, kendati yang kita lihat baru berapa persennya saja. Yang kita lakukan secara kolektif tanpa melihat ras, agama dan aliran adalah melakukan ikhtiar sekuat mungkin dan yang terbaik untuk mencapai cita-cita tersebut.
Di sinilah, kita bisa menengok prinsip dasar yang digunakan dalam mencapai cita-cita tersebut sebagai pedoman dalam pengelolaan pemerintah yang bersih dan berwibawa, sebagaimana berikut:
Pertama, tasharruful imam ‘alar ra’iyyah manutun bil maslahah al-ammah. Kebijakan penguasa atas rakyat didasarkan pada kemaslahatan umum. Penguasa harus mengutamakan rakyat umum, bukan segelintir orang, golongan atau kelompok kepentingan tertentu. Rakyat adalah segalanya. Fox populi fox dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan yang harus didengar dan diwujudkan dalam kehidupan keseharian. Mewujudkan cita-cita rakyat umum adalah sama dengan mewujudkan keinginan Tuhan dalam kehidupan.
Kedua, prinsip dar’ul mafasid ‘ala jalbil mashalih. Artinya, mendahulukan menghindari bahaya daripada melaksanakan kemaslahatan. Penguasa mesti mengupayakan tindakan preventif menghindari bahaya terlebih dahulu dan baru kemudian melaksanakan program yang berbasis kemaslahatan. Prinsip ini bertalian dengan prinsip lain yang berbunyi idza ta’aradla mafsadataani ru’iya a’dlamuha dlararan birtikabi akhaffihima. Apabila terjadi dua bahaya, maka dipertimbangkan bahaya yang paling besar resikonya dengan melaksanakan yang paling ringan resikonya.
Dan Ketiga, prinsip mala yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Maksudnya, kewajiban yang tidak mungkin diwujudkan secara utuh tidak boleh ditinggalkan semuanya. Kita harus menyadari bahwa upaya yang kita lakukan bisa diperoleh secara bertahap dan tidak sekaligus. Apa yang sudah kita capai harus kita syukuri sembari terus melakukan evaluasi untuk senantiasa melakukan perbaikan dan perbaikan. Saya tidak sepakat dengan pernyataan politik beberapa plotisi dan pengamat di beberapa media yang selalu menyudutkan dan (selalu) menyalahkan Indonesia.
Bagaimanapun, untuk mencapai cita-cita Indonesia, tidak mudah semudah membalik telapak tangan. Memperbaiki negeri ini tidak bisa dengan cara hanya mengkritik dan apalagi mencaci maki pengelola negeri ini. Kita harus memulai agenda besar mencapai cita-cita Indonesia ini dengan “bangga menjadi Indonesia”. Indonesia laksana rumah besar bersama kita. Kalau ada yang rusak dan bocor misalnya, mesti kita perbaiki bersama. Dan tentunya, kita tidak perlu merobohkan rumah Indonesia yang kita cintai ini. Selain itu, kita harus melakukan upaya cita-cita kemerdekaan ini secara massif dan progresif di tempat dimana kita berada dan lalu bersinergi satu dengan yang lain dengan tanpa mengabaikan kemajemukan bangsa ini.
Semoga. ***