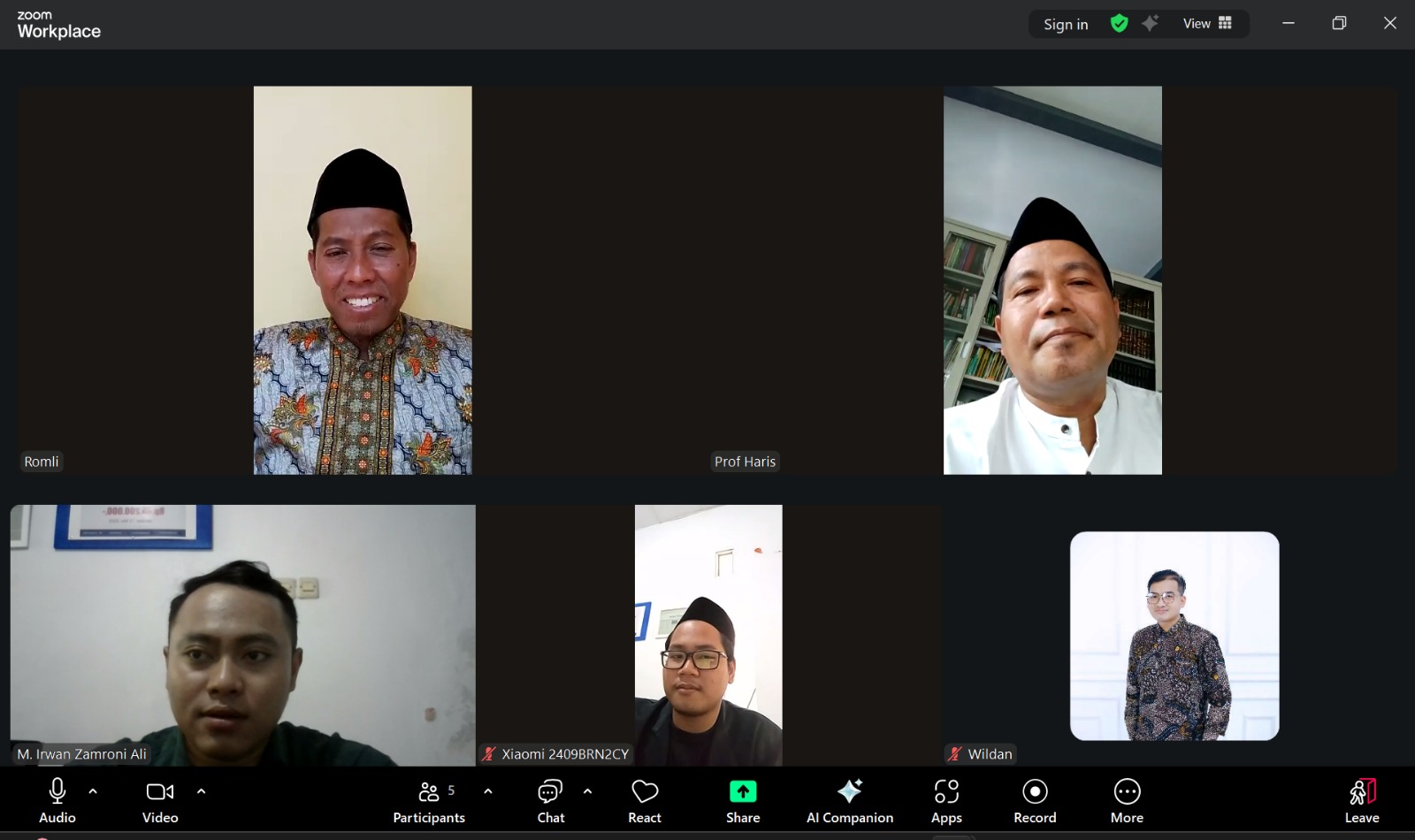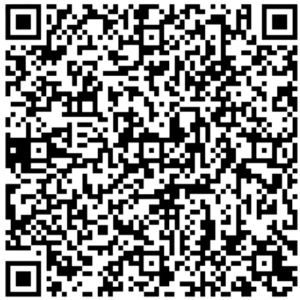Oleh: M. Noor Harisudin (Katib Syuriah PC NU Jember)
GUGATAN terhadap Kompilasi Hukum Islam -selanjutnya disingkat KHI- terus digulirkan. Salah satunya diselenggarakan oleh Kelompok Kajian KHI Tim Pokja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI. Gugatan ini sesungguhnya masuk akal, mengingat KHI yang disusun pada saat rezim Orba berkuasa, mengundang sejumlah masalah.
Masalah ini misalnya bertaut-erat dengan selain eksistensi KHI, juga pada subtansi hukum-nya yang dipandang tidak lagi memadai dalam menyelesaikan pelbagai problematika umat yang sangat kompleks dewasa ini. Alih-alih KHI dapat menyelesaikan pelbagai masalah umat Islam, kalau tidak justru menjadi sumber masalah itu sendiri.
Jika ditelisik lebih dalam, aura visi dan misi KHI -di mana di dalamnya terkandung pasal-pasal mengenai perkawinan, warisan dan perwakafan- memang terdapat beberapa kelemahan pokok. Terlihat, pasal demi pasal dalam KHI yang secara prinsipil bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam yang universal, seperti prinsip persamaan (al-musawah), persaudaraan (al-‘ikha), dan keadilan (al-‘adl). Di samping itu, KHI juga tampak berseberangan vis a vis dengan gagasan dasar bagi pembentukan masyarakat berkeadaban (civil society) seperti pluralisme, kesetaraan gender, HAM, demokrasi dan egalitarianisme, yang menjadi raison d’etre masyarakat Indonesia.
Kelemahan lain yang juga dianggap vital, sebagaimana dinsinyalir oleh sejumlah pakar hukum, adalah KHI memuat ketentuan-ketentuan yang tidak lagi sesuai dengan hukum-hukum nasional dan konvensi internasional yang disepakati bersama. Belum lagi, jika ditelaah dari sudut pandang metodologi, corak hukum yang ditawarkan KHI tampak masih mengesankan replika hukum dari produk fikih jerih payah ulama di masa lampau.
Konstruksi hukum KHI, oleh karenanya, belum dikerangkakan sepenuhnya dalam sudut pandang masyarakat Islam Indonesia, melainkan lebih mencerminkan penyesuaian pada fikih Timur Tengah dan dunia Arab lainnya.
Lihat, misalnya, pada bidang hukum perkawinan. Harus fair diakui bahwa dalam bidang hukum perkawinan KHI, terdapat beberapa pasal problematis dari sudut pandang keadilan relasi laki-laki dan perempuan, seperti batas usia minimal pernikahan (pasal 15 ayat 1). Pasal ini dianggap tidak adil karena telah mematok usia minimal perempuan boleh menikah lebih rendah dari usia laki-laki.
Dengan demikian, pasal ini jelas memperlakukan secara diskriminatif, karena semata-mata didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan laki-laki. Dengan kata lain, kandungan pasal ini sangat berideologi patriarkhis dan sama sekali menanggalkan keadilan gender.
Soal Hak Kewalian
Pasal lain yang juga problematik adalah pasal 19-23 KHI. Berdasarkan penjelasan pasal-pasal tersebut, hak kewalian hanya dimiliki oleh orang yang berjenis kelamin laki-laki.
Sementara, jika sang ayah misalnya berhalangan, ibu tetap tidak diperkenankan menjadi wali nikah atas anak perempuannya. Begitu pula sekiranya sang ayah tidak memungkinkan menjadi wali, maka hak kewalian jatuh pada kakek.
Jika kakek uzur, maka hak kewalian tidak secara otomatis berpindah ke tangan ibu, tetapi turun pada anak laki-laki atau saudara laki-laki sekandung. Hirarki kewalian yang diatur dalam KHI setegasnya menutup sama sekali peluang perempuan untuk menjadi wali, setara dengan larangan terhadap kaum hawa untuk menjadi saksi dalam pernikahan (pasal 24, 25 dan 26 KHI).
Selain itu, soal posisi kepala rumah tangga yang terdapat dalam pasal 79 KHI juga layak direvisi. Dalam pasal ini disebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.
Tampak sekali di sini, jabatan kepala keluarga secara gratis dan otomatis telah diberikan kepada suami tanpa mempertimbangkan kapabilitas dan kredibilitasnya. Dus, para istri hanya diposisikan sebagai ibu rumah tangga yang dipersiapkan hanya mengurusi soal-soal domestik dan tidak memiliki peluang untuk menjadi kepala rumah tangga.
Ketentuan ini tidak saja diskriminatif, tetapi juga tidak sesuai dengan kenyataan sosial yang berkembang di negeri ini, di mana banyak istri yang secara fungsional telah ber-peran sebagai kepala rumah tangga.
Demikian halnya, ikhwal pengaturan nusyuz yang terdapat dalam pasal 84 ayat (1) KHI yang harus pula diperhatikan, menimbang bahwa persoalan ini hanya bertautan dengan perempuan. Oleh sebab itu, pasal ini juga dianggap tidak menunjukkan visi keadilan sosial karena nusyuz yang berlaku bagi dan diperuntukkan kaum perempuan saja.
Sementara, laki-laki atau suami yang mangkir dari tanggungjawab dan kewajibannya tidak dianggap nusyuz dan juga tidak terkena akibat nusyuz. Tidak imbang kiranya, jika mangkirnya suami tidak juga dipandang sebagai nusyuz layaknya kasus perempuan. Tampak di sini, betapa pasal ini terlihat mengekang kebebasan hak-hak perempuan dan tidak mendudukkan hubungan suami-istri secara lebih setara.
Belum lagi dengan ketidakadilan yang terdapat pada hukum kewarisan KHI, seperti dalam pasal 172. Dalam pasal ini, di antaranya disebutkan bahwa bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, harus beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.
Pasal ini seterangnya menyatakan bahwa agama ibu tidak bernilai sama sekali pada anaknya, baik dalam pandangan masyarakat maupun dalam pandangan Tuhan. Padahal, posisi ibu dalam keluarga sangat penting sebagai pendidik dan perambah masa depan anak-anaknya.
Nuansa ketidakadilan dalam hukum kewarisan dapat dijumpai pada pasal 186 tentang status saling mewarisi (dalam kasus anak lahir di luar perkawinan dam kawin sirri) serta pasal 192 dan 193 KHI mengenai radd dan ‘awl.
Edisi Revisi
Melihat berbagai ketidakadilan pasal demi pasalnya, maka sudah selayaknya diajukan KHI edisi revisi yang menggantikan posisi KHI edisi lama. Agenda utama dan pertama dalam pengupayaan KHI edisi revisi ini adalah misalnya dengan memajukan visi yang lebih berkesetaraan gender (al-musawah al-jinsiyyah). Relasi antara laki-laki dan pe-rempuan mesti diletakkan dalam konteks kesetaraan dan keadilan. Ketidakadilan gender, selain bertentangan dengan spirit Islam, juga hanya akan memarginalkan dan mendehumanisasikan perempuan. Padahal, Islam dengan sangat tegas telah memproklamirkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama. Yang membedakan hanya soal ketakwaannya saja.
Visi lain yang harus diutamakan dalam KHI edisi revisi adalah penegakan hak asasi manusia (iqamat al-huquuq al-insaniyyah). Dalam Islam, terdapat sejumlah hak asasi manusia yang harus diusahakan pemenuhannya, baik oleh sendiri maupun negara. Hak tersebut antara lain: hak hidup (hifdz an-nafs), hak kebebasan beragama (hifdz ad-din), hak kebebasan berfikir (hifdz al-aql), hak properti (hifdz al-mal), hak untuk mempertahankan nama (hifdz al-‘irdh) dan hak untuk memiliki garis keturunan (hifdz an-nasl). Sebagaimana disebutkan Imam al-Ghazali dalam kitab ushul fikihnya “al-Mustashfa”, bahwa pada komitmen untuk melindungi hak-hak kemanusiaan di atas inilah, seluruh ketentuan hukum Islam diacukan.
Prinsip lain yang juga semestinya menjadi acuan visi KHI adalah pluralisme (al-ta’addudiyah). Demikian ini penting karena Indonesia adalah negara yang plural. Pluralitas terjadi bukan hanya dari sudut etnis, ras, budaya dan bahasa, melainkan juga agama. Karena itu, pluralitas di negeri ini tidak mengkin bisa dihindari meski juga harus menimbang satu prinsip lain, yakni nasionalitas (al-muwathanah). Makanya, dalam konteks KHI, bukanlah soal pada bagaimana menjauhkan diri dari kenyataan pluralisme tersebut, melainkan pada bagaimana cara dan mekanisme yang diambil dalam menyikapi pluralitas tersebut. Di samping juga, merujuk pada prinsip nasionalitas, tidak lagi ada warga kelas dua, seperti tampak dalam fikih klasik yang mendikotomikan antara muslim dan non-muslim.
Walhasil, senyampang pasal demi pasal KHI bersesuaian dengan prinsip di atas, maka ia tetap layak untuk diteguhkan. Dan sebaliknya, pasal yang berseberangan dengan prinsip di atas, harus dirombak. Wallahu’alam.